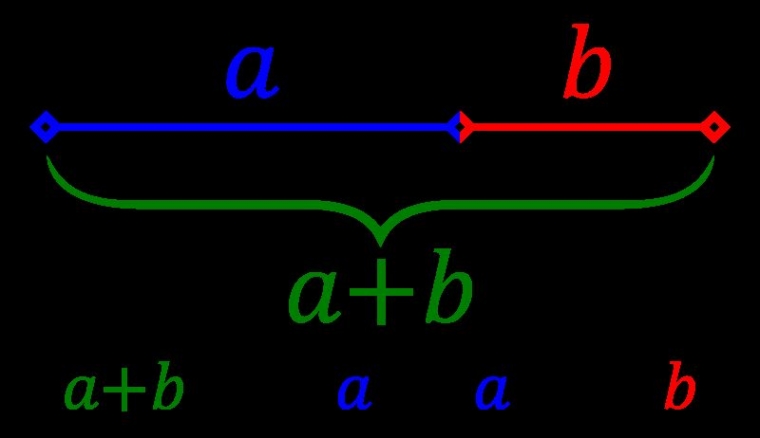Bahasa dan fitur bahasa seperti nama angka dan aksara, merupakan warisan kebudayaan manusia yang telah berusia ribuan tahun. Tapi tahukah kamu jika di dalam fitur bahasa tersebut (khususnya yang digunakan dalam bahasa Indonesia) ternyata terkandung pesan filosofis yang sangat tinggi. Umumnya pesan filosofis tersebut adalah tentang esensi manusia dan kehidupannya.
Dalam tulisan saya sebelumnya (Makna Sakral di Balik Nama-nama Angka) telah saya urai bahwa setelah mencermati penamaan nama angka dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia, terungkap bahwa terdapat pesan filosofis yang sangat tinggi, yang susunan ringkasnya kurang lebih berbunyi: “Satu takdir kemudian dituangkan/ ditempatkan ke dalam wadah yang terbuat dari unsur udara, air, tanah, dan api.“
Sangat jelas bahwa ungkapan rahasia yang tersimpan rapat dan tersamarkan dalam penamaan angka beberapa bahasa daerah di Indonesia ini bercerita tentang eksistensi manusia sebagai entitas yang sepanjang hidup dibayangi takdirnya, sekaligus sebagai entitas materi yang tersusun dari empat unsur utama. (selengkapnya baca di sini)
Filosofi yang terkandung dalam nama angka bahasa Indonesia pun tak kalah luar biasanya. Bahkan formasi penyusunannya yang unik, sebenarnya telah menyiratkan jika ia menyimpan sesuatu makna khusus.
Mari kita cermati…
- Satu (1) dan Sembilan (9), sama-sama huruf awalan S. Jika dijumlahkan, hasilnya: 10
- Dua (2) dan Delapan (8), sama-sama huruf awalan D. Jika dijumlahkan, hasilnya: 10
- Tiga (3) dan Tujuh (7), sama-sama huruf awalan T. Jika dijumlahkan, hasilnya: 10
- Empat (4) dan Enam (6), sama-sama huruf awaln E. Jika dijumlahkan, hasilnya: 10
- Lima (5), huruf awalan L. Lima (5) ditambahkan Lima (5), hasilnya: 10.
Formasi unik yang ditunjukkan pada nama angka dalam bahasa Indonesia ini, pada dasarnya sudah ramai diketahui publik. Hanya saja berhenti pada titik itu saja, tidak mengalami penelusuran lebih jauh ke dalam.
Untuk melanjutkan penelusuran lebih jauh agar dapat memahami makna filosofi yang dikandungnya, memang butuh sedikit kreatifitas.
Hal pertama yang harus dicermati, yaitu huruf awalan yang digunakan pada susunan formasi tersebut, yakni: S, D, T, E, dan L.
Berikutnya, adalah mencermati huruf-huruf tersebut dalam format abjad Yunani. Kenapa mesti begitu? karena jenis abjad latin yang kita gunakan di Indonesia hari ini, bentuk dasarnya adalah dari abjad Yunani. Pada Abjad Yunanilah dimulainya transisi sistem penulisan, yang dari sebelumnya menggunakan sistem penulisan abjad piktograf.
Hasilnya adalah: S = Sigma, D = Delta, T = Tau, E = Epsilon, L = Lambda.

Huruf Yunani, meskipun dapat digunakan layaknya sistem penulisan abjad Latin, tetapi masing-masing hurufnya merupakan suatu simbol yang mengandung makna tersendiri. Jadi, bisa dikatakan huruf Yunani ini tetap memiliki genetik aksara pendahulunya, yaitu piktograf.